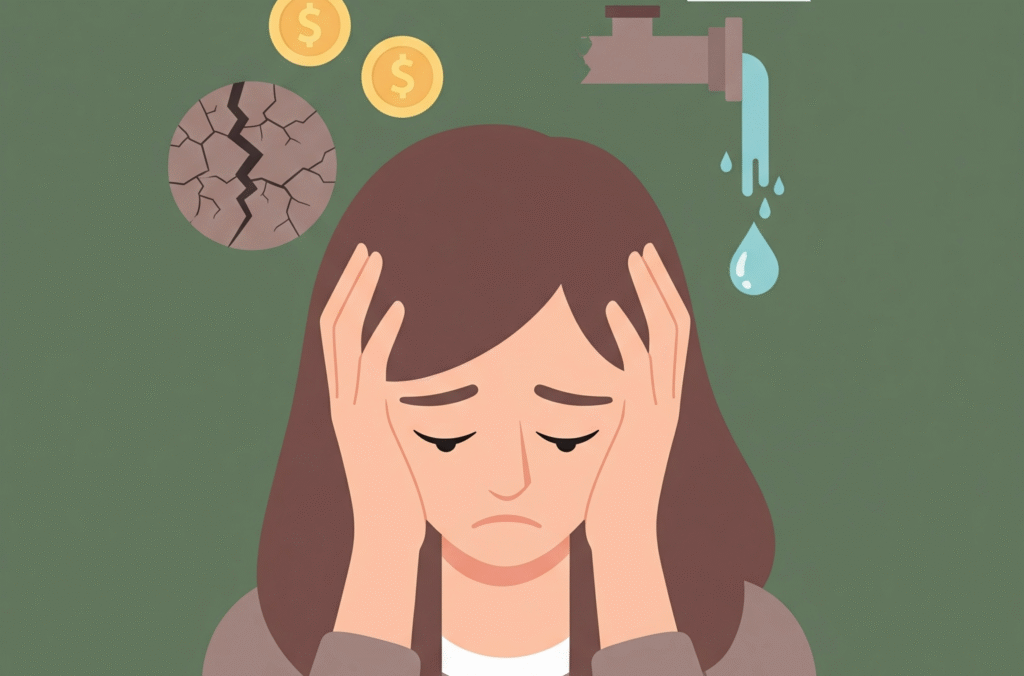
Di tengah hiruk-pikuk Kota Makassar yang terus tumbuh sebagai pusat metropolitan, suara lirih dari pesisir Kecamatan Tallo terus bergema. Air bersih belum hadir secara adil. Selama dua dekade terakhir, para perempuan di wilayah ini, terutama di kampung Galangan Kapal Kaluku Bodoa, Kampung Buloa, dan Makam Raja-raja Tallo, menjadi ujung tombak dalam perjuangan memperoleh akses air bersih yang layak dan terjangkau.
Air adalah kebutuhan dasar, namun bagi sebagian warga Makassar, khususnya perempuan di kawasan pesisir, air bersih justru menjadi barang mewah. Dalam banyak kasus, mereka harus membeli air dengan harga mahal, menempuh jarak jauh, atau menerima kualitas air yang asin dan berbau.
Dari data yang dipublikasikan oleh WALHI Sulsel, di kampung Galangan Kapal Kaluku Bodoa, sebanyak 517 kepala keluarga (KK) diperkirakan mengeluarkan minimal Rp 240.000 setiap bulan hanya untuk mendapatkan air bersih. Artinya, total pengeluaran air bersih di wilayah ini mencapai Rp 124.080.000 per bulan atau lebih dari Rp 1,4 miliar per tahun.
Hal serupa juga terjadi di Kampung Buloa. Dengan jumlah 210 KK, pengeluaran minimal air bersih mencapai Rp 210.000 per bulan per rumah tangga. Total pengeluaran per bulan di wilayah ini mencapai Rp 44.100.000, atau sekitar Rp 529 juta setiap tahunnya.
Kondisi paling mencolok terjadi di Kampung Makam Raja-raja Tallo. Sebanyak 600 KK harus menyisihkan minimal Rp 300.000 per bulan untuk membeli air bersih. Dalam setahun, warga menghabiskan Rp 2,1 miliar hanya untuk kebutuhan dasar tersebut.
Dampaknya sangat dirasakan oleh para perempuan. Mereka tidak hanya menjadi pengelola kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menanggung beban ekonomi tambahan untuk air bersih. Pendapatan mereka yang terbatas tergerus, sementara tubuh dan pikiran mereka terkuras karena harus terus mengupayakan kebutuhan sehari-hari.
Menurut Slamet Riyadi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, ini bukan sekadar soal infrastruktur. Ini tentang ketimpangan sosial dan ketidakadilan akses yang sudah berlangsung terlalu lama. Dalam riset yang dilakukan WALHI, warga Makassar mengungkap berbagai tuntutan penting kepada pemerintah.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 18% warga mendesak agar distribusi air bersih dilakukan secara merata. Sementara itu, 17% meminta pemerintah menghentikan privatisasi dan komersialisasi air yang kian menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebanyak 14% warga berharap pemerintah bersikap lebih serius dalam menyelesaikan persoalan air bersih yang telah mengakar. Mereka tidak ingin janji-janji kosong, melainkan tindakan konkret yang berpihak pada rakyat kecil.
Sementara itu, 13% warga menyarankan agar penggunaan air tanah diperketat untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Sedangkan 9% lainnya menekankan pentingnya menambah ruang terbuka hijau dan resapan air untuk mendukung keberlanjutan sumber daya air.
“Sisanya, 6% warga mendukung pengembangan alternatif sumber air cadangan, termasuk pemanfaatan air hujan, daur ulang air, dan sistem penyimpanan air yang lebih efisien di wilayah padat penduduk,” jelas Slamet Riyadi saat menghadiri pertemua via zoom meeting, Selasa (01/07/2025).
Jenis kesulitan yang dihadapi warga dalam mengakses air bersih pun beragam. Mulai dari air PDAM yang tidak mengalir, air yang harus dibeli dari mobil tangki, hingga kualitas air yang asin, keruh, dan berbau. Di sejumlah titik, sumber air bersih juga sangat jauh dari permukiman.
Bagi para ibu rumah tangga, situasi ini memaksa mereka untuk menyisihkan pendapatan bulanan demi membeli air. Padahal, dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan anak atau kebutuhan pokok lain seperti makanan dan kesehatan.
Ketimpangan ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Pemerintah, dalam hal ini Pemkot Makassar dan PDAM, harus memprioritaskan pembangunan jaringan air bersih di wilayah pesisir dan padat penduduk yang selama ini terabaikan.
“Persoalan air bukan hanya urusan teknis, ini soal hak hidup warga,” tegas Slamet Riyadi. “Kalau pemerintah serius, ini bisa diselesaikan. Tapi jika terus dibiarkan, artinya pemerintah memang tidak berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan.”
Lebih dari sekadar menunggu bantuan, perempuan-perempuan di Tallo terus bergerak. Mereka membuat forum warga, mendesak audiensi, hingga mendokumentasikan persoalan yang mereka alami ke berbagai lembaga.
Namun, suara mereka kerap tenggelam di balik gemerlap proyek-proyek pembangunan kota. Padahal, dalam setiap tetes air yang mereka perjuangkan, tersimpan hak asasi yang seharusnya dijamin negara.
“Sudah saatnya pemerintah mengakui bahwa perempuan pesisir seperti di Tallo bukan sekadar penerima bantuan, tapi pejuang hak atas air. Mereka telah bertahan selama 20 tahun, dan kini menuntut perubahan,” ucapnya.
Jika negara hadir untuk mereka, bukan tidak mungkin Tallo akan menjadi simbol keberhasilan tata kelola air yang adil dan berkelanjutan.
“Tapi jika tidak, maka ketimpangan akan terus tumbuh, dan beban terbesar tetap akan dipikul perempuan-perempuan tangguh di sudut-sudut kota ini,” pungkas Slamet Riyadi.

