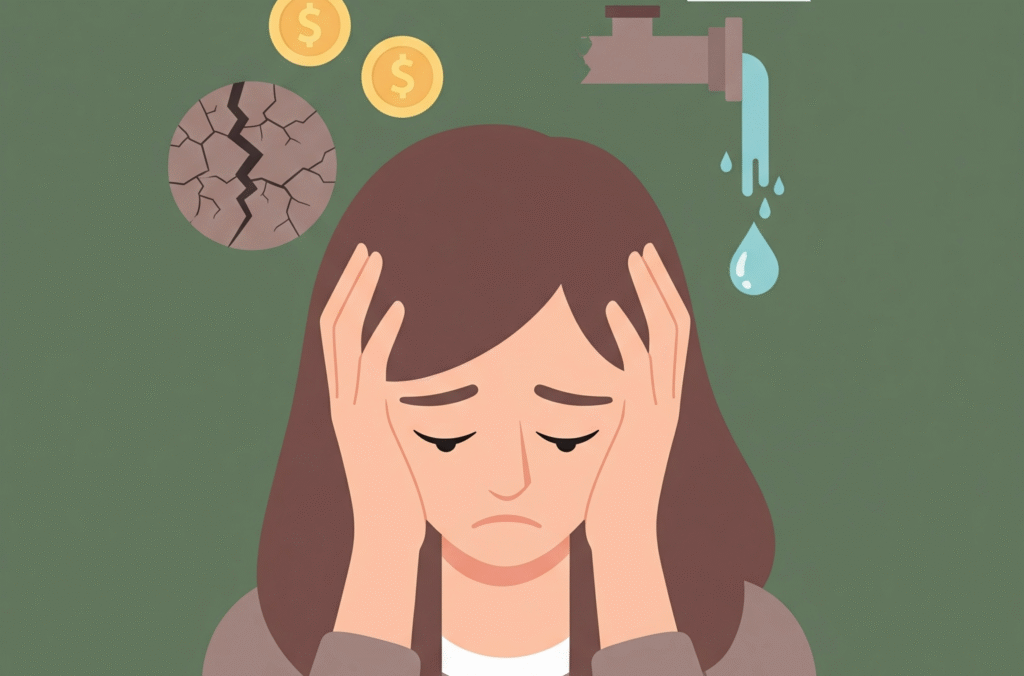Takalar – Sabtu, 23 Agustus 2025, menjadi hari yang tak terlupakan bagi petani Polongbangkeng, Takalar. Ratusan aparat bersenjata lengkap mengepung lahan garapan, bukan untuk melindungi rakyat, melainkan mengawal masuknya alat berat milik PTPN I Regional 8. Bentrokan pun pecah. Suara jeritan bercampur teriakan menolak penggusuran memecah udara.
Hatia Dg Ngenang, seorang perempuan petani, berdiri di barisan depan. Dengan suara lantang ia berseru, “Jangan menebang dulu, ini tanah saya yang diambil perusahaan, dan HGUnya sudah habis!” Namun, jawabannya, hanya tangan kasar aparat yang menarik lengannya ke belakang. Hingga kini tangannya masih bengkak akibat tarikan paksa.
Tak jauh darinya, Dg Serang jatuh tersungkur. Tubuh renta itu diinjak-injak setelah ia berusaha menghalangi mesin yang melaju. Sejumlah petani lain dipukul, ditangkap, bahkan diancam akan dikriminalisasi. Ironisnya, pekerja PTPN yang kedapatan membawa parang dibiarkan begitu saja.
Kemarahan dan kekecewaan memuncak. Bagi para petani, aparat yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi tameng perusahaan.
“Ini bukan sekadar tanah, tapi juga soal hak asasi manusia, hak hidup kami, dan bukti pengkhianatan negara terhadap rakyatnya sendiri,” ujar perwakilan Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah (GRAMT) dalam konferensi pers di Kantor LBH Makassar, yang digelar bersama WALHI Sulsel, Solidaritas Perempuan Angin Mammiri, AGRA Sulsel, dan berbagai organisasi masyarakat sipil.
Ijul, perwakilan AGRA Sulsel, menyebut konflik ini berakar dari sejarah panjang perampasan tanah. “Sejak awal 1980-an, PTPN sudah masuk tanpa persetujuan rakyat. HGU baru keluar tahun 1994, itu pun penuh cacat. Juli 2024 HGU berakhir, artinya mereka tidak punya dasar hukum lagi. Tapi nyatanya, perusahaan masih beroperasi dengan kawalan aparat,” tegasnya.
Sebelumnya, warga bahkan masih bersabar. Mereka membiarkan PTPN menyelesaikan panen terakhir, dengan harapan tanah segera dikembalikan. Namun janji itu tak pernah ditepati. Polres Takalar bukannya menghentikan aktivitas ilegal, malah ikut mengawal jalannya penebangan.
Kini, wajah Polongbangkeng penuh luka. Luka fisik dari pukulan dan injakan, juga luka batin karena tanah leluhur dirampas di depan mata. Konflik agraria yang terjadi di Takalar ini kembali memperlihatkan pola klasik, yaitu tanah rakyat dikuasai perusahaan, hukum diabaikan, dan aparat bersenjata menjadi pagar besi untuk kepentingan korporasi.