“Perempuan adat berada di garis depan ekonomi keluarga, tapi justru mereka yang paling jauh dari akses digital,” kata Mustaqim.
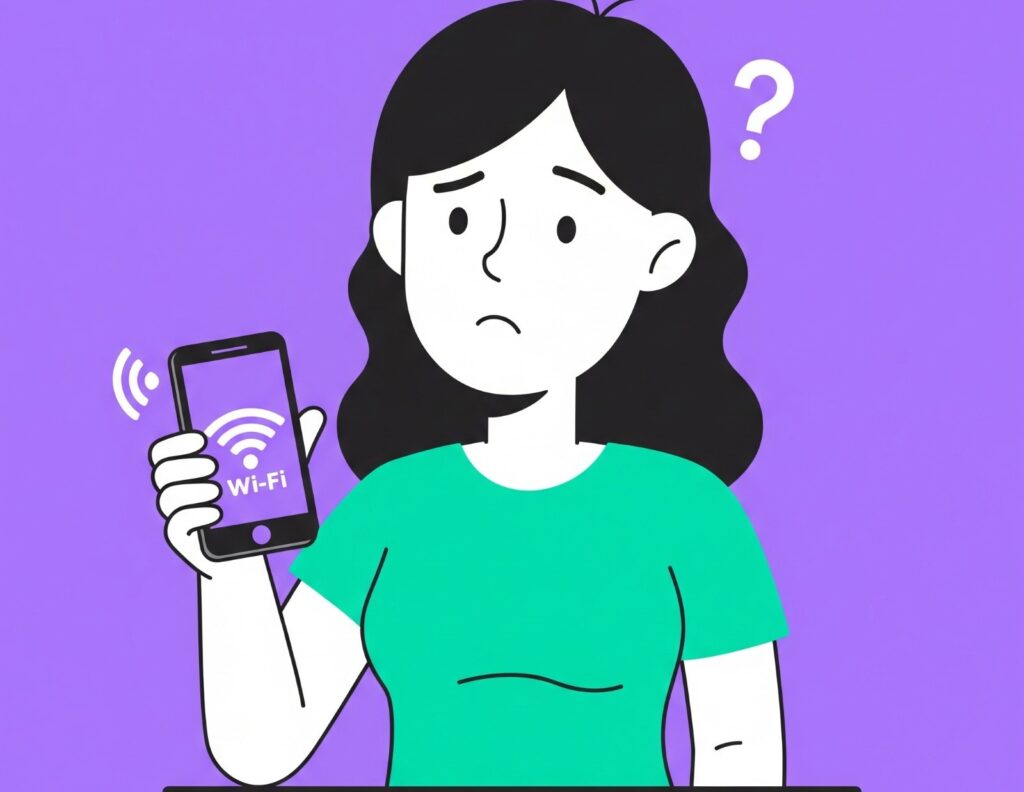
Gowa, Sulsel — Di balik narasi besar tentang transformasi digital Indonesia, masih banyak komunitas masyarakat adat atau masyarakat adat sendiri yang belum tersentuh arus perubahan itu. Salah satunya adalah kelompok masyarakat adat di pelosok Sulawesi Selatan, tepatnya di Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Gowa.
Di sana, masyarakat khususnya perempuan adat masih terbatas soal akses internet, infrastruktur digital, bahkan literasi teknologi dasar.
Tak hanya itu, mereka pada dasarnya masih menghadapi keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Sehingga tidak heran jika akses informasi digital yang saat ini telah menjadi menjadi kebutuhan pokok zaman modern, justru menjadi hal yang terpinggirkan di sana.
“Di kampung kami, jaringan sudah bagus. Tapi, banyak ibu-ibu yang belum tahu mengakses digital seperti WA. Atau hal yang mendasar seperti mendaftar layanan bantuan digital pemerintah kami juga banyak yang tidak tahu,” ujar Nuraini, seorang perempuan adat dari pegunungan di Kabupaten Gowa.
Perlebar Jurang Ketimpangan
Digitalisasi harusnya membuka ruang partisipasi, tapi kenyataannya justru memperlebar jurang ketimpangan. Program-program pelatihan digital jarang menyasar wilayah adat. Ketika dunia berbicara tentang AI, e-wallet, dan literasi digital, banyak perempuan adat bahkan belum memahami dasar penggunaan ponsel pintar.
Minimnya infrastruktur seperti sinyal, listrik, dan perangkat juga menjadi kendala utama. Ditambah dengan minimnya pendekatan budaya dalam edukasi teknologi, masyarakat adat, terutama para perempuan, merasa asing dan ditinggalkan.
“Kalau kami tidak bisa ikut pelatihan online, bukan karena tidak mau belajar. Tapi karena memang tidak bisa mengaksesnya,” lanjut Nuraini.
Keterpinggiran Digital
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya bentuk baru ketidakadilan: keterpinggiran digital.
Jika dibiarkan, perempuan adat akan semakin tertinggal dalam berbagai aspek. Mulai dari peluang usaha berbasis online hingga akses layanan kesehatan berbasis aplikasi.
Pemerintah dan lembaga non-pemerintah perlu merancang program digitalisasi yang berbasis inklusi budaya. Bukan sekadar menggelar pelatihan di kota, tapi hadir di tengah komunitas adat dengan pendekatan lokal, bahasa ibu, dan kesetaraan gender.
Digitalisasi tidak boleh melupakan mereka yang paling jauh. Sebab, perempuan di masyarakat adat bukan hanya penonton perubahan, mereka penjaga nilai, penggerak komunitas, dan seharusnya, pemilik masa depan digital yang adil.
Tantangan Digitalisasi Masyarakat Adat: Antara Harapan dan Peluang
Menurut Mustaqim, Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PH AMAN) Gowa, sebagian wilayah seperti Bulutana dan Parigi mulai mengenal penggunaan QRIS dan e-wallet, terutama mereka yang bersinggungan langsung dengan konsumen modern atau wisatawan.
Namun, di banyak wilayah lain seperti Kecamatan Tombolo Pao, transaksi masih sepenuhnya dilakukan secara tunai dan tradisional.
“Ini bukan karena mereka menolak teknologi,” jelas Mustaqim,
“Tetapi karena sistem ekonomi komunal belum siap terhubung secara digital,” ujarnya.
Bagi perempuan adat, tantangan ini berlapis. Mereka tidak hanya harus mengelola rumah tangga dan menjaga warisan budaya, tetapi juga menghadapi keterbatasan literasi digital dan finansial.
Dalam banyak kasus, mereka bahkan belum pernah menggunakan smartphone secara aktif, apalagi mengoperasikan aplikasi keuangan.
“Perempuan adat berada di garis depan ekonomi keluarga, tapi justru mereka yang paling jauh dari akses digital,” kata Mustaqim.
Padahal, data Bank Indonesia mencatat 78 juta transaksi QRIS di Sulsel sepanjang 2024. Sayangnya, capaian ini belum menyentuh kehidupan mayoritas masyarakat adat, terutama para perempuan di dalamnya. Banyak dari mereka belum memahami konsep e-wallet, QRIS, apalagi risiko penipuan digital.
“Banyak informasi hanya berputar di kalangan elit lokal. Perempuan-perempuan adat jarang disentuh oleh edukasi yang tepat. Saat ada penipuan digital, baru mereka tahu setelah menjadi korban,” ungkap Mustaqim.
Mustaqim menyoroti pendekatan digitalisasi yang selama ini bersifat top-down dan seringkali tak memperhitungkan konteks budaya lokal.
“Inovasi teknologi akan diterima kalau pendekatannya tepat: menghargai kultur, menggunakan bahasa yang dimengerti, dan menjangkau perempuan-perempuan adat secara langsung,” jelasnya.
Bank Indonesia, sebagai institusi yang mendorong inklusi keuangan, didorong untuk lebih aktif turun ke komunitas adat. Program literasi dan edukasi digital seharusnya tidak berhenti di kepala desa atau perangkat formal, melainkan menyentuh langsung perempuan adat yang menopang kehidupan komunitas sehari-hari.
Mustaqim menekankan bahwa membentuk ekosistem digital inklusif berarti memahami siapa yang tertinggal dan mengapa.
Perempuan Bukan Objek Pasif
“Perempuan adat bukan objek pasif digitalisasi. Mereka pelaku, penjaga nilai, dan pemegang peran ekonomi. Tapi selama mereka tidak dilibatkan secara aktif, maka digitalisasi hanya akan memperlebar jurang ketimpangan.”
Ia pun merekomendasikan adanya program literasi digital berbasis komunitas, dengan pendekatan yang peka budaya dan gender.
“Kalau ingin inklusif, maka perempuan adat harus jadi bagian dari perubahan, bukan hanya penonton,” ujarnya.
PENULIS: GITA OKTOVILA

